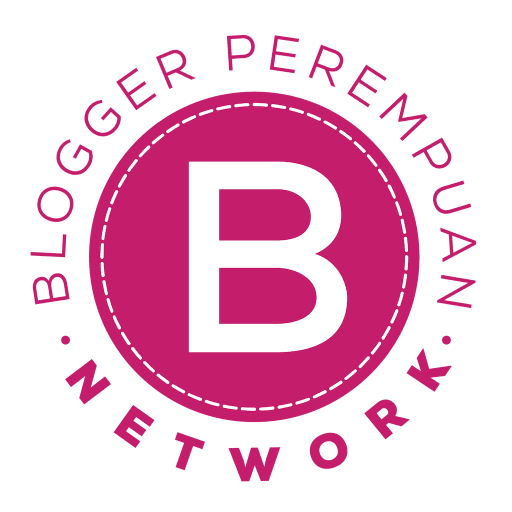|
Bermula dari link yang pernah dishare
@ikanatassa di Twitternya, yaitu sebuah artikel di www.buzzfeed.com mengenai The Urban Poor You Haven’t Noticed: Millenials Who’re
Broke, Hungry But On Trend yang ditulis oleh Gayatri Jayaraman dari India. (sorry but the link is broken, but you still can search about it)
Dalam artikelnya, ia (Gayatri Jayaraman) menjabarkan
betapa ia mengasihani para urban poverty
yang hidup sengsara di balik gengsi, tentang bagaimana mereka (urban poverty) menjalani keseharian dengan
was-was dan rasa lapar yang mendera, tentang kebutuhan sekunder dan tersier
yang menjadi prioritas dibandingkan dengan kebutuhan primer, tentang life style
penuh pencitraan.
Awalnya aku mengira fenomena (yang kini
disebut) urban poverty hanya terjadi
di Indonesia saja, atau wilayah Asia pada umumnya. Tapi setelah membaca artikel
tersebut aku menyadari bahwa urban poverty adalah fenomena global yang cukup mengkhawatirkan.
Urban
poverty atau yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia
adalah kaum urban (masyarakat yang
tinggal di perkotaan) miskin adalah sebuah fenomena nyata yang terjadi saat
ini. Dimana kaum urban yang
seharusnya bisa menikmati hidup adem ayem bisa menjadi miskin hanya karena
gengsi.
Di Indonesia sendiri, jika tinggal di daerah Jawa
Barat yang notabene masyarakatnya gemar bersosialisasi, pasti pernah mendengar kalimat
“paribasa geus digawe ...” yang dalam terjemahan bebasnya bisa diartikan
sebagai ”istilahnya sudah bekerja ...”.
Kalimat tersebut ditujukan untuk menyindir
orang yang sudah bekerja namun masih hidup pas-pasan. Intinya sih menuntut agar orang yang disindir
itu mau sedikit pamer, meski sekedar membayarkan ongkos angkot temannya atau terlihat
memakai pakaian dengan model terbaru.
Ada anggapan bahwa yang bekerja pastilah
(selalu) berduit. Entah itu bekerja
sebagai karyawan, PNS, freelancer atau
buruh sekalipun. Selalu ada tuntutan sosial dimana mereka harus menampilkan
hasil jerih payahnya, semacam “ini loh,
hasil kerja di anu ... “.
Bahkan tak jarang anggota keluarga juga ikut
berpartisipasi. Demi menjaga gengsi gaji bulan pertama, ada orang tua yang rela
mengeluarkan uang agar anaknya bisa mentraktir makan teman-temannya,
sepupu-sepupunya atau bahkan keluarga besarnya. Mengatakan itu adalah hasil
kerja si anak, meski kenyataannya gaji tersebut masih jauh dari kata UMR (Upah
Minimum Rata-rata).
Kalau mau tahu seberapa besar efek urban poverty, lihatlah bagaimana kehidupan buruh (worker) di daerah. Smartphone
terbaru, kendaraan pribadi yang masih mulus, dandanan yang stylish, tempat nongkrong yang hits
dan sifat konsumtif adalah hal yang biasa. Namun di balik semua itu, ada
petugas leasing dan rentenir yang
menanti. Kadang-kadang ...
Ada orang tua yang curhat tentang anaknya yang masih suka meminta uang meski
sudah bekerja, ia tak habis pikir
kemana perginya gaji si anak, mempertanyakan apa bedanya sekolah dan bekerja kalau
masih tetap dibiayai orang tua?
Mungkin si anak akan menjawab “on my body ...” atau “on my face ...” sambil bergaya dan
menunjuk wajah. LOL
Ketika masa OJT (On
Job Training), salah satu (mantan) atasanku bertanya “how many percentage of your salary that would you give to your parents?”
yang aku jawab dengan “it’s depends on
situation Sir”, ia bertanya lagi “so
your parents is working right?” aku menjawab “yes” karena kedua orang tuaku masih bekerja, setelah mendengar
jawabanku ia berkata “off course you are”.
Ia kemudian
bercerita bahwa di Korea ada peraturan tersendiri mengenai gaji untuk karyawan baru
atau fresh graduated. Jika orang tua karyawan tersebut tidak bekerja (tidak
menghasilkan uang) maka sepersekian persen dari gajinya akan ditransfer ke
rekening orang tuanya, ia bisa mendapatkan gajinya secara full hanya jika orang tuanya bekerja.
Karena tanpa bantuan
dan dukungan dari orang tua, anak tersebut tidak akan menjadi seperti ini
(bekerja) dan sepersekian persen dari gaji adalah bentuk rasa terimakasih dan
tanggungjawab. It’s a nice habit ... tapi mungkin jika diterapkan di Indonesia
akan menuai pro dan kontra besar-besaran, meski masih jadi wacana.
Orang tuaku pernah bertanya
kenapa aku tidak menggunakan gajiku seperti anak-anak temannya, membeli pakaian
baru, sepatu baru, tas baru, make up
baru, pergi nongkrong dengan teman-teman, pergi jalan-jalan dengan pacar dan
hal lain yang anak-anak temannya lakukan ketika sudah bekerja.
Aku tidak melakukan
hal-hal yang tidak ku sukai hanya karena orang lain melakukannya. Aku lebih
suka menabung serta membelanjakan sisa gajiku untuk membeli buku terbaru dan sketch tools. Membeli pakaian baru, sepatu baru, tas
baru dan make up baru bukanlah suatu keharusan di setiap bulannya, begitu
pun dengan nongkrong dan jalan-jalan. Membaca blog dan artikel di internet jauh lebih berharga daripada
sosialisasi haha hihi.
Karena ikan Salmon
tidak perlu mengikuti arus untuk menjadi diri sendiri.
Aku melihat temanku membeli pakaian baru,
sepatu baru, tas baru dan make up
baru di setiap bulannya, pada suatu hari ia mengeluh tentang betapa ‘trendy
is
pain’
. Ia sangat trendy, tapi dengan gaji
yang pas-pasan ia hanya mampu membeli yang biasa saja, katakanlah low quality. Ia berasumsi, selama
mengenakan model terbaru, orang tidak akan pernah mengetahui berapa harganya.
Kenyataannya, hampir
semua barang trendy kebanggaannya rusak setelah dipakai beberapa kali, ia harus
terus menerus berbelanja setiap bulan untuk menutupi kebutuhannya. Dengan
‘sampah’ yang bertambah setiap bulannya, ia merasa telah jatuh miskin, menyadari
bahwa sebenarnya ia tidak memiliki apa-apa.
Dosenku pernah
berkata: jika ingin menjadi designer
harus wise dan kuat iman, karena
profesi tersebut adalah yang paling dekat dengan neraka. Tahu kenapa? Karena ia
(designer) harus mampu untuk
membangkitkan naluri terendah dalam diri manusia yaitu lust dan desire. Dan
sebaik-baiknya designer adalah yang
mampu mendesign produk yang
memunculkan rasa ingin memiliki hanya dengan melihatnya. Seperti love at the first sight (with sins following after).
Mungkin urban poverty muncul akibat designer atau creativepreneur yang sangat produktif.
Semacam ‘our
goals is your poverty’.